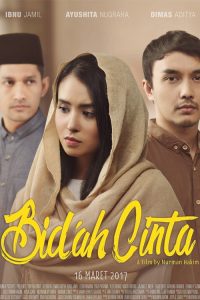Aksi damai 212 di Tugu Monas Jakarta pada tanggal 2 Desember 2016 lalu, menginspirasi Helvy Tiana Rosa untuk membuat film adaptasi dengan judul 212 the Power of Love. Helvy, penggagas utama film ini, mengatakan bahwa film 212 tak ada kaitannya dengan kepentingan politik tertentu. Film ini murni terinspirasi dari aksi damai 212 yang telah memutihkan Jakarta.
Film yang disutradarai oleh Jastis Arimba ini dibangun dari kisah ketidakharmonisan antara seorang ayah dan anaknya. Melalui kisah tersebut, Film 212 ingin menunjukkan bahwa Islam bukanlah agama yang keras dan radikal sebagaimana dipahami oleh sebagian masyarakat. Kekhawatiran – atau lebih tepatnya kecurigaan – masyarakat selama ini dijawab dengan gamblang melalui tuturan cerita yang dikemas secara dramatis dan apik.
Sebuah kisah tentang perjalanan hidup seorang jurnalis majalah Republik, alumnus terbaik Harvard University bernama Rahmat (Fauzi Baadillah). Dia dikenal sebagai penulis cerdas dan idealis. Namun kali ini, tulisannya tentang rencana aksi damai 212 dianggap dapat menyinggung umat Islam dan mengadu domba masyarakat.
Dalam tulisannya, Rahmat menyebut rencana aksi 212 ditunggangi oleh kepentingan politik tertentu. Agama dijadikan alat untuk mencapai tujuan-tujuan politik. Tentu saja, pemimpin redaksi dan sejumlah temannya khawatir jika tulisan ini dilempar ke ranah publik akan mengancam kelangsungan bisnis media mereka, bahkan pihak redaksi harus siap berhadapan dengan jutaan umat Islam.
Rahmat lahir dari keluarga santri. Dia adalah putra Ki Zainal (Humaidi Abbas), seorang kiyai kampung dari Ciamis. Hubungan Rahmat dengan ayahnya tidak harmonis. Bahkan Rahmat tidak pernah pulang ke rumah sejak 10 tahun terakhir. Namun karena mendapat kabar ibunya meninggal, Rahmat terpaksa pulang kampung. Di sinilah konflik cerita bermula.
Rahmat memiliki hubungan buruk dengan ayahnya sejak kecil, yaitu sejak ia dipondokkan di sebuah pesantren. Dia menganggap ayahnya kurang peduli dengannya saat di pesantren. Dia tidak pernah dijenguk, kecuali oleh ibunya. Saat mendapat beasiswa kuliah di Harvard pun, ayah Rahmat tak menunjukkan kebanggaannya sebagaimana umumnya seorang ayah yang bangga terhadap anaknya yang berprestasi. Inilah yang membuat Rahmat berontak dan berkali-kali membuat ulah. Namun ayahnya berdalih bahwa ketidakpeduliannya karena kenakalan Rahmat sejak kecil. Bahkan kematian dua saudara Rahmat dianggap bagian dari ulahnya.
Rahmat semakin tidak simpati dengan ayahnya karena menjadi penggerak masyarakat untuk melakukan aksi 212 di Monas Jakarta. Dia yang sejak awal membenci aksi tersebut, berulang kali mencegah ayahnya agar membatalkan rencana konyolnya. Tapi sia-sia. Ki Zainal, yang bermain sangat bagus dalam film ini, keukeuh melanjutkan perjalanan aksi bersama para pemuda dan warga kampung. Meski begitu, Rahmat selalu berada disamping ayahnya saat melakukan perjalanan ke Jakarta. Dia menuntun ayahnya saat terjatuh, bahkan memandikan saat kaki ayahnya sulit bergerak. Meskipun sebenarnya dada Rahmat bergemuruh dan kesal terhadap ayahnya yang keras kepala itu.
Film ini sedikit dari film nasional yang berani mengangkat persoalan masyarakat secara kritis, terutama kaitannya dengan isu sosial, agama, dan politik. Sekalipun demikian, film yang didukung oleh pemain Adhin Abdul Hakim, Hamas Syahid, Meyda Safira, dan Asma Nadia ini cukup objektif. Cerita film dikemas secara cover both sides dalam menarasikan realitas di masyarakat. Ini yang banyak diabaikan oleh film-film bertema Islam lainnya.
Objektivitas pembingkaian ini tampak dalam menyikapi kasus hujatan, cibiran, atau cemoohan sebagian masyarakat terkait isu agama. Misalnya, saat sejumlah peserta aksi 212 mengecam Rahmat dengan sebutan munafik, maka melalui tuturan Yasna (Meyda Sefira), seorang umat Islam tidak boleh dengan mudah menyebut orang munafik atau mengkafirkan saudara sesama Muslim. Karena Tuhanlah yang berhak menyebut seseorang itu kafir atau munafik. Tugas seorang Muslim adalah memberitahu dan mengajak pada yang ma’ruf bagi mereka yang belum mengetahui. Bukan sebaliknya, menghujat mereka yang berujung pada permusuhan.
Adegan ini sekaligus membantah bahwa semua para peserta aksi 212 adalah mereka yang mudah menghujat dan berpotensi melakukan aksi kekerasan. Di sinilah objektivitas film terlihat jelas. Di satu sisi, film 212 tak menafikkan bahwa memang ada sejumlah peserta aksi 212 yang mudah menghujat atau mengkafirkan sesama saudara Muslim. Namun di sisi lain, perbuatan tersebut tidak dibenarkan dalam Islam sebagaimana yang dituturkan oleh peserta aksi 212 lainnya, yaitu Yasna. Bahkan seorang nonmuslim pun harus diperlakukan sama dalam hal kemanusiaan.
Sayang, alur cerita yang dikemas dengan menarik justru kurang “nendang” pada klimaksnya. Jika saja Ki Zaenal meninggal saat shalat berjamaah di depan Monas, maka penonton akan semakin diharu biru. Di situlah puncak klimaksnya. Hal lain yang cukup mengganggu adalah dandanan Yasna – yang diperankan Meyda Sefira dengan cukup baik. Polesan wajahnya terlalu menor untuk ukuran gadis kampung. Namun demikian, kisah cinta Yasna dan Rahmat sebagai bumbu dalam film ini cukup dapat, tanpa harus disampaikan secara vulgar. Secara teknis, editing (cutway) gambar dalam film ini kurang mulus. Terutama ketika memasukkan gambar peristiwa aksi 212 di Monas Jakarta (dokumentasi asli) ke dalam adegan masyarakat Ciamis yang telah sampai di Jakarta.

Lepas dari kelemahan teknis tersebut, film ini sangat layak ditonton. Tidak hanya bagi alumni 212 sebagai ajang reuni, tapi juga bagi masyarakat umum yang selama ini hanya menyimak pemaparan dari media mainstream dan online. Pesan persaudaraannya cukup terasa. Ada tiga kata yang pantas untuk film 212 the Power of Love yaitu berani, damai, dan objektif!